BAB I
PENDAHULUAN
2.1. Latar Belakang
Antropologi adalah
suatu ilmu yang memahami sifat-sifat semua jenis manusia secara lebih banyak. Manusia menciptakan kebudayaan karena
kebudayaannya manusia hidup berbudaya. Kebudayaan mempengaruhi atau membangun
kepribadian seseorang atau suatu bangsa melalui cara-cara pendidikan.
Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran, pemberian
pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pikiran, karakter serta kapasitas
fisik dengan menggunakan pranata-pranata agar tujuan yang ingin dicapai dapat
dipenuhi. Dalam masyarakat yang sangat kompleks, terspesialisasi dan berubah
cepat, pendidikan sangat memiliki peran besar dalam memahami kebudayaan sebagai
satu keseluruhan. Dengan makin cepatnya perubahan kebudayaan, maka makin banyak
waktu untuk memahami kebudayaannya sendiri.
Masyarakat
dan bangsa Indonesia bersifat majemuk. Kemajemukan sosial budaya pada suku-suku
bangsa di Indonesia di satu pihak merupakan kebanggaan, tetapi di pihak lain
juga dapat menimbulkan kesulitan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang
merata dan menyeluruh, khususnya di bidang pendidikan. Sehubungan dengan itu,
para pendidik perlu mempelajari antropologi pendidikan.
Untuk
memahami konsep tentang kebudayaan dan pendidikan, karakteristik fisik,
lingkungan fisik, dan kemajemukan sosial budaya Indonesia, maka disusunlah
makalah ini. Di samping itu, makalah ini juga bertujuan untuk memahami
implikasi kebudayaan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.
2.1.
Rumusan Masalah
1.2.1.
Bagaimana arti dan konsep tentang kebudayaan?
1.2.2.
Bagaimana hubungan antara kebudayaan dengan kepribadian?
1.2.3.
Bagaimana hubungan kebudayaan dengan pendidikan?
1.2.4.
Bagaimana karakteristik fisik manusia Indonesia?
1.2.5.
Bagaimana karakteristik lingkungan fisik manusia Indonesia?
1.2.6.
Bagaimana profil kemajemukan sosial budaya Indonesia?
1.2.7. Bagaimana implikasi
profil karakteristik sosial budaya Indonesia terhadap penyelenggaraan
pendidikan?
1.3 Tujuan
1.3.1.
Mahasiswa dapat menjelaskan arti dan konsep kebudayaan.
1.3.2.
Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara kebudayaan
dengan kepribadian.
1.3.3.
Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara kebudayaan
dengan pendidikan.
1.3.4.
Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik fisik manusia
Indonesia.
1.3.5.
Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik lingkungan fisik
manusia Indonesia.
1.3.6.
Mahasiswa dapat menjelaskan profil kemajemukan sosial budaya
Indonesia.
1.3.7.
Mahasiswa dapat menjelaskan implikasi profil karakteristik
sosial budaya Indonesia terhadap penyelenggaraan pendidikan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. KEBUDAYAAN, KEPRIBADIAN, dan PENDIDIKAN
2.1. Konsep Kebudayaan
2.1.1 Definisi Kebudayaan
Dalam arti sempit kebudayaan adalah
kesenian, yaitu pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya
akan keindahan. Adapun dalam arti luas kebudayaan adalah seluruh
total dari
pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berkar kepada nalurinya karena itu hanya bias dicetuskan
oleh manusia sesudah suatu proses belajar. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan
hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari
manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1984). Selo
Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengemukakan kebudayaan adalah semua
karya dari cipta rasa dan karsa masyarakat. Budaya juga didefinisikan seluruh
hasil usaha manusia dengan budinya berupa segenap jiwa yakni cipta, rasa dan
karsa.
2.1.2
Unsur-Unsur Universal Kebudayaan
Menurut
Koentjaraningrat (1984) terdapat 7 unsur universal kebudayaan, yaitu sebagai berikut.
a) Sistem religi dan upacara keagamaan.
b) Sistem organisasi kemasyarakatan.
c) Sistem Pengetahuan
d) Bahasa
e) Kesenian
f) Sistem mata pencaharian hidup
g) Sistem teknologi dan peralatan
Tata
nama unsure-unsur universalkebudayaan di atas mengambarkan kontinum dari
unsure-unsur yang paling sukar berubah ke unsure-unsur yang paling mudah
berubah.
2.1.3 Wujud Kebudayaan
Kebudayaan paling
tidak memiliki 3 wujud,
yaitu sebagai berikut,
a) Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu
kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.
b) Wujud system sosial, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu
kompleks berpola dari manusia dalam
masyarakat.
c) Wujud fisik, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda
hasil karyamanusia.
2.1.4. Hubungan Antara
Wujud-Wujud Kebudayaan
Kebudayaan ideal memberi arah kepada perbuatan dan
karya manusia
baik pikiran-pikiran dan ide-ide maupun perbuatan dan karya manusia menghasilkan
benda-benda kebudayaan
fisiknya. Sebaliknya
kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin
menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi pola pikirnya.
2.1.5. Penggolongan
Kebudayaan
Supardi Suparlan
(A.W. Widjaja,
1986) membedakan kebudayaan menjadi 3 golongan, yaitu :
a) Kebudayaan Suku bangsa (yang lebih dikenal dengan nama Kebudayaan Daerah)
b) Kebudayaan umum lokal
c) Kebudayaan Nasional
2.1.6. Sifat atau
Karakteristik Kebudayaan
a) Organik dan super organik. Kebudayaan bersifat organic sebab kebudayaan berakar pada organ manusia,
tanpa manusia berbuat, berpikir, merasa dan membuat benda-benda maka tidak aka ada kebudayaan. Kebudayaan super organik karena kebudayaan hidup terus melampaui
generasi tertentu dan arena isinya lebih merupakan hasil karya manusia daripada hasil unsur
biologis.
b) Overt (terlihat) dan covert (tersembunyi). Kebudayaan terlihat dalam bentuk-bentuk tindakan-tindakan dan
benda-benda, seperti
rumah, pakaian, bentuk pembicaraan yang dapat diamati
secara langsung. Sedangkan tersembunyi, yakni dalam aspaek sikap dasar
terhadap
alam fisik dan alam gaib yang mesti diiterprestsikan pengertiannya dari apa yang dikatakan dan dilakukan
anggota-anggotanya.
c) Ideal dan aktual (manifest). Kebudayaan ideal terdiri atas cara berbuat/ berkelakuan sesuai dengan kepercayaanya
(normative),
sedangkan
bersifat actual (manifest) maksudnya kebudayaan itu merupakan tindakan-tindakan yang nyata.
d) Stabil dan berubah. Terdapat hal-hal dipertahankan oleh
masyarakat
agar tidak tetap berubah (stabil), tetapi terjadi pula perubahan-perubahan kebudayaan di dalam masyarakat. Para antropolog umumnya menerima
ketidak tetapan
kebudayaan.
2.1.7. Fungsi Kebudayaan
Kerber dan Smith (Imran Manan, 1989)
mengemukakan fungsi utama kebudayaan dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut :
a) Pelanjut keturunan dan pengasuhan anak
b) Pengembang kehidupan ekonomi
c) Transmisi budaya
2.2 Kebudayaan dan Kepribadian
2.2.1 Kepribadian dan Kepribadian Bangsa
Kepribadian adalah susunan
unsure-unsur akal dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan
dari setiap individu manusia. Kepribadian tersebut ada 2 jenis yaitu kepribadian
yang menunjuk kepada seorang individu dan kepribadian bangsa contohnya:
kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian individu terbentuk didalam lingkungan
hidupnya sepanjang hidup individu yang bersangkutan. Oleh Karena itu, upaya
memahaimi kepribadian tanpa menghubungkan dengan konteks lingkungan hidupnya
akan merupakan gambaran mati yang kurang berarti.
2.2.2 Manusia Menciptakan Kebudayaan dan karena Kebudayaannya Berbudaya
Kebudayaan membentuk manusia secara
intelektual, emosiaonal, secara fisik atau tingkah laku manusia. Mengingat hal
tersebut dan dengan mengacu kepada pengertian kepribaidan sebagaimana telah
dikemukakan diatas maka dapat dipahami adanya hubungan antara hubungan antara
kebudayaan dengan kepribadian, yaitu bahwa kebudayaan berpengaruh atau
membangun kepribadian seseorang.
2.2.3. Pendidikan atau Enkulturasi
Kebudayaan
mempengaruhi manusia melalui apa yang disebut dengan enkulturasi atau
internalisasi budaya yaitu suatu proses dimana seorang individu menyerap cara
berpikir, bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaannya. Enkulturasi
berlangsung didalam berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan
pergaulan didalam masyarakat. Dalam arti luas, bahwa pendidikan atau
enkulturasi berlangsung dalam kehidupan dan sepanjang hayat.
2.3 Kebudayaan dan Kependidikan
Antara kebudayaan dan pendidikan terdapat
hubungan komplementer. Pertama kebudayaan berperan sebagai masukan dan
pendidikan contohnya tujua pendidikan ditentukan oleh system nialai yang dianut
oleh masyarakat. Kedua pendidikan berfungsi untuk melestarika kebudayaan
masyarkat dan juga berfungsi dalam rangka melakukan pengemabangan dan atau
perubahan kebudayaan masyarkat kearah yang lebih baik. Fungsi konservasi atau
pelestarian kebudayaan merupakan fungsi kependidikan dlam rangka pewarisan
kebudayaan. Hal yang harus diwariskan kepada genersi muda tentunya adalah
kebudyaan ideal (misalnya nilai kejujuran, keadilan, pola perilaku baik, dan
sebagainya) sehingga klebudayaan ideal milik masyarakat menjadi lestari. Fungsi
kreasi atau inovasi dan pendidikan merupakan fungsi untuk diciptakannya
kebudayaan baru yang lebih baik, sesui dengan tuntutan kehidupan, dan
perkembangan jaman.
B. KARAKTERISTIK DAN KEMAJEMUKAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA
2.4. Karakteristik Fisik Suku-Suku Bangsa Indonesia
Para sarjana Antropologi
menggolongkan manusia ke dalam tiga ras pokok berdasarkan perbedaan wujud fisik
yang nyata, yaitu ras Kaukasoid (putih), ras Mongoloid (kuning), dan ras
Negroid (hitam). Menurut Agraha Suhandi (1985), suku bangsa Indonesia dapat digolongkan
ke dalam tiga ras. Masing-masing ras tersebut sebagai berikut:
1.
Ras Negroid
(Negrite): berkulit hitam, rambut keriting, tinggi badan kurang lebih 1,50 m,
kepala pendek. Unsur ras ini masih tampak antara lain pada suku bangsa Iriyan
Jaya (Papua).
2.
Ras Vedoid (Wedda):
kulit sawo matang, rambut ikal atau bergelombang, tinggi badan kurang lebih
1,50 m, bentuk kepala panjang (Dolicho Cephali). Unsur ras ini masih tampak
pada suku bangsa Enggano, Kubu, Dayak Barito, Toala di Sulawesi, mentawai, Nias
dan tampak sedikit pada sebagian kecil suku bangsa Batak.
3.
Ras Mongoloid: ras
Mongoloid di Indonesia kadang-kadang disebut juga ras Melayu dengan
karakteristik kulit sedikit kunibg, rambut lurus, tinggi badan kurang lebih
1,50 m, bentuk kepala pendek (brachichephali). Suku bangsa yang memperlihatkan
karakteristik ras ini merupakan sebagian besar yang sampai sekarang terdapat di
Indonesia. Ras Melayu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Proto Melayu dan
Deutero Melayu.
2.5. Karakteristik Lingkungan Fisik Manusia Di Indonesia
Tuhan menganugerahi masyarakat Indonesia
lingkungan fisik yang luas, bervariasi, dan mengandung kekayaan yang luar biasa
sebagai sumber daya alam bagi pembangunan yang mendukung bagi pencapaian
kemakmuran. Lingkungan fisik yang beriklim tropis sangat kopndusif untuk
pertanian dan pada umumnya tanahnya pun subur (tetapi ada daerah-daerah yang
tidak subur seperti di pulau Flores); mempunyai berbagai sumber mineral, sumber
minyak, hutan kayu, kekayaan laut, gunung berapi, keragaman tumbuhan, keragaman
satwa. Selain itu, lingkungan fisik masyarakat (bangsa) kita memiliki keindahan
tersendiri. Masyarakat Indonesia sepatutnya bersyukur kepada Tuhan YME,
memanfaatkan kekayaan lingkungan fisik tersebut dengan mengolahnya secara
bijaksana agar kelestariannya dan keutuhannya tetap terjaga demi kesejahteraan
seluruh masyarakat Indonesia.
2.6 Kemajemukan Sosial-Budaya Bangsa Indonesia
Antropologi
Indonesia, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa “Bangsa Indonesia yang mendiami
kepulauan Nusantara ini merupakan sebuah masyarakat majemuk, baik dalam hal
suku bangsa, agama yang dianutnya, adat istiadat atau lebih umum lagi dalam hal
kebudayaannya”.
Untuk lebih
mendapatkan gambaran kemajemukan masyarakat dan kebudayaan Indonesia, berikut
ini akan dideskripsikan enam unsure kebudayaan universal beberapa suku bangsa
yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :
1.
Pola perkampungan
/Desa
Suatu kesatuan tempat
tinggal yang disebut kampung demikian pula perluasannya, seperti desa bagi
suku-suku bangsa di Indonesia memiliki pola yang berbeda-beda. Pola-pola kampung
di suatu daerah kadang kala menunjukkan adanya beberapa pola tergantung dan
keadaan lingkungan dimana kampung atau desa itu berada. Dengan demikian, tidak
mungkin untuk mengatakan pola kampung tertentu merupakan pola yang khas untuk
suatu suku bangsa, sebab kenyataannya setiap suku bangsa memiliki pola
kampung/desa campuran. Contohnya: Pola kampung suku bangsa Sunda ada yang
berderet, berkelompok dan ada pula yang memiliki tanah lapang dilengkapi dengan
lumbung padi, saung lisung (tempat menumbuk padi), kandang ternak, balong
(kolam), dan pancuran (tempat mandi atau cuci). Pola kampung suku bangsa Jawa
ditandai dengan adanya rumah-rumah beserta pekarangan yang satu dengan yang
lain dipisahklan dengan pagar bam,bu atau pagar hidup. Ada di antara rumah
tersebut dilengkapi dengan lumbung padi, kandang ternak, dan perigi.. kampung
yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan jalan kampung. Rumah-rumah
berjajar menghadap ke jalan.
2.
Sistem Kemasyarakatan
System kemasyarakatan
di Indonesia dalam arti kepemimpinan formal dalam pemerintahan dari tingkat
provinsi sampai dengan kecamatan adalah sama. Namun, kepemimpinan pada tingkat
desa atau kampung dalam konteks kebudayaan suku bangsa atau daerah cukup
beragam.
3. System Kekerabatan
Kekerabatan ialah istilah yang
digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat berkenaan dengan
penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatanmasing-masing dengan
ego. Terdapat cara menarik garis garis keturunan masyarakat Indonesia, antara
lain :
a) Matrilineal : Suku bangsa Minangklabau dan Enggano
b) Patrilineal : di daerah pegunungan Aceh, Buru, Seram, Ambon,
Kepulauan Kei, Aru, dan suku bangsa Batak.
c) Dobel Unilateral atau matri-patrilineal : Suku bangsa Rejang
dan sebagian suku bangsa Sumba.
d) Parental atau
Bilateral : Suku bangsa Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Jawa, Sunda,
Madura, Sulawesi, Riau, Bangka Belitung.
4.
Sistem Mata
Pencaharian Hidup
Masyarakat (bangsa) Indonesia
mempunyai keragaman juga dalam system mata pencaharian hidupnya. Memang Negara
kita terkenal sebagai Negara agraris, tetapi dalam bercocok tanam terdapat
berbagai cara yang dilakukan kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi
lingkungan fisik dan budayanya, seperti berladang, bertegalan, dan bersawah.
Selain dari hidup petani, di antara masyarakat Inmdonesia juga ada yang bermata
pencaharian melalui beternak, sebagai nelayan, perikanan darat, perikanan
tambak, dan berdagang. Ada juga yang yang mengusahakan kerajinan dan
pertenunan.
5.
Bahasa dan Kesenian
Bangsa Indonesia memang mempunyai bahasa
persatuan-kesatuan, yaitu Bahasa Indonesia. Namun demikian, hampir setiap suku
Bangsa di Indonesia memiliki bahasa ibu atau bahasa daerahnya masing-masing.
Contohnya kita mengenal bahasa Sunda, bahas Batak, bahasa Melayu, bahasa
Padang, bahasa Bugis, bahasa Jawa.
Kesenian pun demikian beragamnya di Indonesia. Hal ini baik
berkenaan dengan music, nyanyian, tarian, kerajinan tangan, yang menjadi cirri
khas setiap suku bangsa atauy daerah masing-masing. Contohnya : seni pahat atau
seni ukir dari Jepara, Bali, Irian Jaya; batik Pekalongan, Batik Garutan,
Tasikmalaya, dsb; tari Sunda, tari Bali, tari Betawi, dsb.
6.
Sistem Agama atau
Kepercayaan
Di
antara masyarakat Indonesia ada yang menganut agama Islam, Kristen Protestan,
Kristen Katholik, Hindu Bali, Budha, Kong Hu Cu. Namun demikian, dalam praktik
kehidupan sehari-hari tampak unsure-unsur kepercayaan tyang berada di luar
agama-agama tersebut di atas. Berkenaan dengan ini Agraha Sugandi (1985)
mengemukakan bahwa hampir pada setiap suku bangsa dikenali adanya mite atau
mitologi, yaitu kepercayaan tentang kejadian dari sesuatu, misalnya tentang
alam semesta, manusia, tentang mengapa matahari selalu terbit dari timur,
tentang kejadian padi, dan kejadian dari tempat-tempat tertentu. Dari mite
tersebut dapat diketahui kepercayaan dari suku-suku bangsa tersebut bahwa
segala sesuatu tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi ada yang
menyebabkannya atau menciptakannya.
C. IMPLIKASI KARAKTERISTIK MANUSIA INDONESIA TERHADAP
PENDIDIKAN
2.7. Implikasi
Terhadap Dasar dan Akar Pendidikan
Pancasila adalah jiwa
seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa
Indonesia, dan sebagai dasar Negara Indonesia. Implikasinya maka Pancasila dan
UUI 1945 berkedudukan sebagai dasar pendidikan nasional.
Pendidikan harus
dikembangkan dengan berakar kepada nilai-nilai agama dan kebudayaan bangsa
tersebut. Jika tidak demikian maka pendidikan tidak akan dapat meningkatkan
kualitas hidup bangsa secara utuh. Demikian pula jika pendidikan dilaksanakan
dengan berakar pada kebudayaan bangsa lain, tentu akan menimbulkan kesenjangan
sosial-budaya. Bahkan mungkin identitas bangsa tersebut akan terkikis habis dan
muncul masyarakat baru yang terputus dari dimensi kesejarahan kebudayaan
bangsanya. Implikasinya maka pendidikan nasional hendaknya berakar pada
nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional.
2.8. Implikasi Terhadap Pengelolaan Pendidikan
Pengelolaan pendidikan
bersifat Dekonsentrasi. Mengingat betapa luasnya wilayah Negara Republik
Indonesia serta keanekaragaman keadaan lingkungan fisik dengan segala kekayaan
yang dikandungnya, dan majemuknya keadaan sosial-budaya di Indonesia maka perlu
diambil suatu kebijakan di dalam pengelolaan pendidikan agar efisien dan
efektif. Implikasinya maka kebijakan pengelolaan pendidikan dalam system
pendidikan nasional kita bersifat dekonsentrasi seperti tercermin dalam pasal
50 UU RI No. 20 Tahun 2003.
2.9. Kurikulum Pendidikan
Kurikulum Berbasis
Kompetensi. Keragaman dan kekayaan lingkungan fisik yang dimiliki masyarakat
(bangsa) Indonesia akan kurang dimanfaatkan bagi kemakmuran apabila masyarakat
tersebut kurang berdaya untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya. Oleh sebab itu,
pendidikan hendaknya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Implikasinya maka kurikulum pendidikan
hendaknya merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi.
Kurikulum Nasional
dan Kurikulum Muatan Lokal. Ragamnya lingkungan fisik yang dihuni masyarakat
Indonesia, serta ragamnya keadaan sosial-budaya menghadapkan suatu tantangan
bagi masyarakat (bangsa) Indonesia. Antara lain : (1) pelestarian integrasi
bangsa yang bersifat majemuk agar tetap Bhinneka Tunggal Ika, (2) terbinanya
kepribadian bangsa Indonesia, (3) standar nasional mutu pendidikan, dan (4)
relevansi pendidikan secara nasional, serta (5) relevansi pendidikan secara
local sesuai dengan keadaan lingkungan dan sosial budaya daerah atau suku
bangsa yang bersangkutan. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa integrasi adalah
keserasian satuan-satuan yang terdapat dalam suatu system (bukan penyeragaman,
tetapi hubungan satuan-satuan sedemikian rupa dan tidak merugikan masing-masing
satuan).
Implikasi dari semua
hal di atas maka perlu diambil kebijakan untuk tersedianya : pertama, kurikulum
nasional yang memungkinkan tetap lestarinya keadaan masyarakat yang Bhinneka
Tunggal Ika, terbinanya kepribadian Bangsa, terjaminnya standar nasional mutu
pendidikan, dan relevansi pendidikan secara nasional. Kedua, kurikulum muatan
local yang memungkinkan terjaminnya relevansi pendidikan secara local, baik
dalam kaitannya dengan lingkungan fisik maupun sosial-budaya.
2.10.
Wajib Belajar
Presiden RI telah
mencanangkan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Jadi, wajib belajar ini
lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di SD atau satuan
pendidikan yang sederajat dan tiap tahun SLTP atau satuan pendidikan yang
sederajat.
Ditinjau dari sudut
antropologi, yaitu berkenaan dengan dengan karakteristik sosial budaya
Indonesia terdapat beberapa hal yang turut berimplikasi terhadap kebijakan dan
penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar ini, di antaranya :
1) Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa.
2) Nilai dan norma yang mengakui kesamaan hak setiap warga
Negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana termaktub pada Pasal 31 UUD
1945.
3) Keragaman lingkungan fisik masyarakat Indonesia yang
sebagian besar berada di pedesaan terpencil dan terisolasi.
4) Pelapisan sosial-ekonomi (yaitu tinggi, menengah, dan rendah
atau miskin), dimana dalam masyarakat Indonesia masih cukup jumlah masyarakat
miskin.
5) Asumsi mengenai fungsi pendidikan demi pembudayaan dan
pemberdayaan masyarakat.
6) Asumsi mengenai fungsi kebudayaan sebagai dasar dan alat
bagi manusia untuk dapat menangani permasalahan dan memenuhi kebutuhan
hidupnya.
2.11.
Gerakan Nasional
Orang Tua Asuh
Pelaksanaan
pendidikan memerlukan dana atau biaya yang memadai. System sosial masyarakat
Indonesia terdapat pelapisan sosial-ekonomi, yang terdiri atas : lapisan
masyarakat kaya, menengah, dan miskin. Khususnya masyarakat miskin untuk dapat
membiayai anak-anaknya agar dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat sekolah
dasar saja sudah sulit atau bahkan tidak mampu. Apalagi untuk menyelesaikan
wajib belajar Sembilan tahun. Di pihak lain pemerintah pun memiliki
keterbatasan dalam hal anggaran pendidikan. Sementara mereka mendapatkan
jaminan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kewajiban belajar
pendidikan dasar Sembilan tahun.
Pemerintah melalui Keputusan Menteri
Sosial RI No. 52/HUK/1996 telah mengambil keputusan tentang “Pembentukan
Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh”. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
(GN-OTA); dan dikeluarkan pula Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1997
tentang “Pembentukan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh”.
2.12.
Implikasi
Karakteristik Kebudayaan Terhadap Praktek Pendidikan
Kebudayaan memiliki
karakteristik ideal dan actual, serta stabil dan berubah. Karakteristik
kebudayaan ini tentunya berlaku juga dalam kebudayaan masyarakat Indonesia.
Karakteristik kebudayaan ini mengandung potensi untuk memunculkan masalah dalam
praktik pendidikan. Tentu saja dengan syarat apabila tidak ada kesejalanan
antara kebudayaan actual dan kebudayaan idealnya. Demikian pula mungkin terjadi
konflik antara kebudayaan baru dengan kebudayaan yang dianggap sudah stabil
atau mapan.
Pancasila
dan UU 1945 adalah dasar pendidikan kita, implikasinya kita memang perlu
melestarikan kebudayaan lama yang dianggap mapan, sebaliknya juga tidak menolak
perubahan. Prinsip perubahan dalam pendidikan bukanlah mengikuti perkembangan
zaman atau kebudayaan yang sedang berubah melainkan melakukan perubahan dengan
mengacu kepada nilai-nilai dasar tertentu dan mengendalikannya kea rah tujuan
tertentu pula.
BAB III
KESIMPULAN
Setelah mengerjakan makalah ini, kami
dapat menarik kesimpulan bahwa :
1) Manusia menciptakan
kebudayaan dan karena kebudayaannya manusia hidup berbudaya. Kebudayaan mempengaruhi
(membangun) kepribadian seseorang. Kebudayaan mempengaruhi atau membangun
kepribadian melalui enkulturasi atau pendidikan.
2) Kemajemukan bangsa
Indonesia meliputi karakteristik fisiknya, karakteristik lingkungan fisiknya,
dan sosial budayanya.
3) Implikasinya bahwa
Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar bagi pendidikan nasional sebagai salah
satu pranata kebudayaannya.
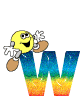
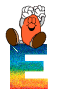
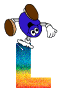
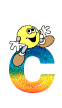
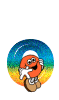
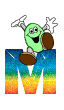
Tidak ada komentar:
Posting Komentar